*Untuk melihat semua artikel Sejarah Indonesia Jilid 1-10 di blog ini Klik Disini
Jika ditanya AI: Prasasti tertua di Indonesia adalah
Prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai, yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti
ini ditemukan di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur, dan ditulis dalam bahasa
Sanskerta dengan aksara Pallawa. Prasasti Yupa menjadi bukti keberadaan
kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Bagaimana
dengan sejarah Indonesia versi Ptolomeus abad ke-2?
Semenanjung Emas (bahasa Yunani: Χρυση χερσόνησος; bahasa Latin: Chersonesus Aurea) adalah nama kuno yang digunakan oleh geografer Ptolomeus (c. 90 M – c. 168 M) untuk menyebut Semenanjung Malaya. Nama ini merupakan terjemahan dari Suvarnadvipa dalam bahasa Sanskerta. Marinus dari Tyrus juga menggunakan istilah ini, tetapi karena dvipa bisa berarti "semenanjung" atau "pulau", geografer Eratosthenes, Dionysius Periegetes, dan Pomponius Mela memutuskan untuk menerjemahkan Suvarnadvipa menjadi "Pulau Emas". Semenanjung Malaya dulu memiliki reputasi di dunia internasional sebagai sumber emas. Martin Behaim, di globe buatannya tahun 1492, mencantumkan pulau Chryse dan Argyre ("Emas" dan "Perak") di dekat Zipangu (Jepang) yang menurut Marco Polo "kaya akan emas". Sebuah ekspedisi dikirim ke daerah ini untuk menemukan dua pulau tersebut pada tahun 1587 di bawah pimpinan Pedro de Unamunu (Wikipedia). Word origin: L chersonesus; Gr chersonēsos; chersos, dry land; +nēsos, island).
Lantas bagaimana sejarah sejarah Indonesia versi Ptolomeus abad ke-2? Seperti disebut di atas, di dalam teks Geographia, ditulis Ptolomeus abad ke-2 terdapat wilayah yang diberi nama Aurea Chersonesus dimana di pantai baratnya diidentifikasi nama (tempat) Tacola dan Cocconagara. Apakah tiga nama tersebut di (semenanjung) Malaya? Lalu bagaimana sejarah Indonesia versi Ptolomeus abad ke-2? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.
Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja. Dalam hal ini saya bukanlah penulis sejarah, melainkan hanya sekadar untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta (kejadian yang benar pernah terjadi) dan data tertulis yang telah tercatat dalam dokumen sejarah.
Sejarah Indonesia versi Ptolomeus Abad ke-2; Apakah Tacola, Cocconagara Aurea Chersonesus di Malaya?
Nama Indonesia pertama kali diusulkan James Richard Logan pada tahun 1850. Logan merujuk pada kombinasi Indu+nesos yang kemudian akhirnya dipilihnya kombinasi Indo+nesia yang menjadi Indonesia. Dalam hal ini nesos atau nesia artinya kepulauan. Sejak Logan mempublikasikan nama itu di jurnal The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Sejak itu, nama Indonesia lambat laun dijadikan para sarjana dan peminat Hindia Belanda sebagai nama identitas suatu wilayah: kepulauan Hindia menjadi kepulauan Indonesia.
Bagaimana James Richard Logan menemukan nama Indonesia? Satu yang jelas di Eropa sudah lama nama Chersonesos dibicarakan oleh para akademisi. Ada yang menyebut Chersonesos adalah Italia atau Spanyol dan tentu saja ada yang menolaknya. Orang Yunani tidak akan menyebut Italia dan Spanyol sebagai Chersonesos, tetapi Xegoóvyoos, suatu daratan yang terhubung ke daratan utama oleh tanah genting yang sangat sempit. Dalam hal ini sarjana Jerman yang paling banyak menyoal nama itu, termasuk Theodor Panofka dalam bukunya berjudul Von dem Einfluss der Gottheiten auf die Ortsnamen yang diterbitkan tahun 1842 dan Ludolf Stephani dalam bukunya berjudul Ueber "Beitrage zur Geschichte und Archäologie von Cherronesos in Taurien hrsg. von B. v. Köhne" yang diterbitkan tahun 1949. Tentu saja kata Chersonesos yang disebut berasal dari Ptolomeus masuk dalam kamus lama seperti Thesaurus antiquitatum et historiarum Siliciae, quo continentur yang ditulis oleh Joannes Georgius Graevius yang diterbitkan tahun 1725.
Sudah barang tentu, James Richard Logan tidak asing
dengan penamaan Chersonesos dalam bidang geografi. Namun begitu, James Richard Logan di tempat
sunyi (di Singapore) mulai memikirkan apa yang tepat untuk menamai Indien atau
Indische
Archipel oleh penulis-penulis Belanda (yang orang Inggris mengejanya dengan Indian
Archipelago). Nama Indien atau Indische Archipel/Indian Archipelago tersebut tampaknya
kurang pas bagi James Richard
Logan sehingga mulai memikirkan nama yang tepat yang kemudian mengusulkan nama
Indonesia (lihat The Ethnology of the Indian Archipelago by James Richard Logan
yang dimuat pada edisi IV tahun 1850 Journal of the Indian Archipelago and
Eastern Asia).
Perdebatan penamaan Chersonesos di Eropa adalah satu hal. Diskusi penamaan Indonesia di Kepulauan Hindia adalah hal lain lagi. Dalam hal inilah para sarjana dan peminat Hindia di Batavia mulai mendiskusikan soal kepurbakalaan termasuk nama yang terus hangat didiskusikan di Eropa: Chersonesos. Hal itu bermula dengan penemuan-penemuan kepurbakalaan di Jawa dan Sumatra yang kemudian diuraikan oleh Prof. R H Th Friederich di Batavia pada tahun 1857 yang dimuat dalam jilid ke-XXVI Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (99 hlm plus 4 lampiran dengan tiga gambar). Tulisan Prof. R H Th Friederich, ahli studi bahasa Jawa kemudian disarikan majalah ilmiah di Belanda Algemeene konst- en letter-bode, voor het jaar, jrg 71, 1858, No. 22, 29-05-1858). Editor kemudian meminta komentar Chr. Lassen guru besar di Bonn. Prof Christian Lassen sendiri baru saja menebitkan buku berjudul Indische Alterthumskunde (1858) yang didalamnya juga membahasa Chersonesos. Prof Christian Lassen kemudian merespon editor tersebut dan tanggapannya dimuat dalam volume ke-13 Zeitschrift der entschen morgenlandischen Gesellschaft, 1859, hlm. 310 yang lalu disarikan Algemeene konst- en letter-bode, voor het jaar, jrg 73, 1861-1862, No. 1, 05-01-1861. Intinya Prof Lassen mengatakan bahwa Friederich telah memperoleh banyak jasa melalui risalahnya yang dirujuk di sini "mengenai sejarah Jawa dan Sumatera yang lebih tua, karena untuk pertama kalinya ia secara akurat mengungkap dan menjelaskan dengan cermat tiga prasasti pulau-pulau tersebut, dan telah membawa data yang berguna dari beberapa teks lain, yang melaluinya, seperti dari prasasti yang disebutkan pertama, sebuah cahaya baru dipantulkan pada kondisi kedua pulau sebelumnya. Lassen sepenuhnya setuju dengan pandangan Sumatera harus diakui di pulau Jabadioe milik Ptolemeus. Menurutnya, lokasi pulau di sebelah barat Malaka (Chryse Chersonesos) tidak memungkinkan pandangan itu. Sumatera, dianggap oleh Lassen sebagai sesuatu yang berbobot, Lassen juga menganggap dugaan Eriederioh, dalam catatan di hlm. 81, bahwa Kepulauan Sabadiben yang disebutkan oleh Ptolemeus (Sabadei nesoi) mewakili pengucapan nama Jawa yang lebih baru Akhirnya, Lassen memuji ketelitian Friederich dalam memberikan penjelasan, baik dari pembacaan prasasti yang diberikan olehnya, dan dari perubahan yang diajukan di dalamnya sekarang dan kemudian. Kepastian itu tidak segera diperoleh di mana-mana, bahwa semua pembacaan dan perubahan tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak akan mengejutkan siapa pun yang mempertimbangkan bagaimana Friederich pindah ke sini di daerah yang sebelumnya hampir tidak dapat diakses, bahkan ia harus disebut sebagai orang pertama yang memasukinya.
Prof. R H Th Friederich adalah orang pertama yang membuka penyelidikan Chersonesus di Hindia yang kemudian diyakini Prof Chr Lassen berada di Sumatra. Dari namanya besar kemungkinan kedua guru besar ini berasal dari Jerman. Sementara para sarjana di Eropa masih bingung alias belum menemukan bukti dan argumentasi yang kuat tentang dimana itu Chersonesos, seperti halnya James Richard Logan tentang nama Indonesia, Prof Friederich dan Prof Chr Lassen mulai pikiran mereka masing-masing bekerja di tempat sunyi (baca: di Indonesia).
Pada awal mula pelayaran pelaut-pelaut Eropa ke berbagai tempat, termasuk ke Hindia pada abad ke-15, teks Geographia yang ditulis Ptolomeus abad ke-2 menjadu salah satu rujukan bagi pelaut-pelaut. Para kartografer Eropa mulai menyusun peta-pea baru, apakah dari hasil penyelidikan mereka di berbagai perpustakaan maupun laporan-laporan pelaut Portugis dan Spanyol yang baru tiba dari tempat yang jauh. Untuk wilayah timur jauh, dua peta Ptolomeus yang menarik perhatian umum adalah letak pulau Aurea Chersonesus dan letak pulau Taprobana. Silang pendapat nama Aurea Chersonesus adalah Semenanjung Malaya, Sumatra dan Jawa di satu sisi dan nama pulau Tabrobana adalah Ceylon dan Sumatra. Seiring dengan laporan-laporan pelaut Portugis yang sudah sampai di Indonesia pada tahun 1511 (dimulai di Malaka), para kartografer di Eropa percaya bahwa pulau Taprobana versi Ptolomeus dalah pulau Sumatra (lihat Peta 1565 di atas—pulau Sumatra disebut juga Taprobana dibuat oleh seorang Italia Giovanni Battista Ramusio)). Akibatnya, nama Aurea Chersonesus mulai dihubungkan hanya mengarah (sebatas) Semenanjung Malaya (lihat Peta 1561). Dua nama yang berasal dari era Ptolomeus pada abad ke-2 seakan sudah ditemukan. Hampir tidak ada lagi yang mendiskusikan dua nama (tempat) itu lagi. Apalagi peta-peta baru oleh para kartografer dari kontribusi pelaut-pelau Portugis dan Spanyol seluruh muka bumi sudah dijelajahi dengan diberi nama (baru) pada peta. Nama Ptolomeus Kembali masuk laci. Dalam konteks inilah, setelah sekian lama muncul dua sarjana dan sama-sama peminat Hindia: Prof Friederich dan Prof Chr Lassen.
Singkatnya, bahkan hingga kini, dimana letak sebenarnya Aurea Chersonesos dan Taprobana masih terus jadi perdebatan. Hal itu pula mengapa artikel ini ditulis. Dalam peta Ptolomeus yang berasal dari abad ke-2, di wilayah yang disebut Aurea Chersonesos diidentifikasi dua nama tempat di pantai barat: Tacola dan Cocconagara. Hipotesis saya dimulai dari dua nama tersebut yang diduga sebagai dua nama kota di pantai barat Sumatra.
Pada peta Ptolomeus abad ke-2, baik Aurea Chesonesus maupun Taprobana diidentifikasi dengan garis ekuator. Ini mengindikasikasikan kedua nama tempat itu berada di garis khatulistiwa. Ini sesuai dengan pulau Sumatra dan pulau Kalimantan pada masa ini. Hal itulah diduga mengapa para kartografer pada abad ke-16 menganggap Taprobana versi Ptolomeus adalah pulau Sumatra yang dilalui garis ekuator (Peta 1565). Namun yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan peta Taprobana versi Ptolomeus. Fakta bahwa dalam peta Ptolomeus Aurea Chersonesus adalah terkesan sebagai suatu semenanjung, sementara Taprobana sebagai suatu pulau tunggal. Lalu para kartografer menganggap Aurea Chersonesus adalah (sebatas) Semenanjung Malaya (Peta 1561).
Tacola dan Cocconagara dihipotesiskan sebagai dua nama kota di pantai barat Sumatra karena secara toponimi nama Tacola mirip dengan nama Akkola atau Angkola yang sekarang (wilayah Tapanuli Selatan). Sedangkan Cocconagara mirip dengan nama Kunkun yang sekarang (nama kota di Mandailing Natal). Tentu saja pendekatan toponimi tidak cukup, dan harus dibuktikan dengan pendekatan lainnya. Lantas bagaimana Tacola dan Cocconagara dianggap berada di pantai barat Sumatra.
Perhatikanlah (kembali) peta Prolomeus untuk (semenanjung) Aurea Chersonesus. Dalam peta ini diidentifikasi garis sungai yang membelah semenanjung. Garis (imajiner) sungai di sekitar garis ekuator membelah semenanjung menjadi empat bagian. Satu bagian pertama di utara ekuator di sebelah timur diduga adalah Semenanjung Malaya; sementara satu bagian di utara ekuator di sebelah barat adalah (pulau) Sumatra (bagian utara). Sedangkan satu bagian di selatan ekuator di sebelah barat adalah (pulau) Sumatra (bagian selatan). Satu bagian lagi yang tersisa di selatan adalah pulau Bangka/Belitung (akan dijelaskan nanti). Jadi, dalam hal ini, identifikasi garis imajiner sungai pada dasarnya adalah perairan (laut/selat atau sungai). Garis imajiner sungai yang membelah Sumatra bagian utara dan bagian selatan diduga adalah dua sungai besar di pantai barat Sumatra dan di pantai timur Sumatra yang dianggap bersatu.
Dengan mengasumsikan bahwa pulau Sumatra pada peta Ptolomeus terbagi dua (utara dan selatan) di sekitar garis ekuator, maka Tacola dan Cocconagara diduga berada di pantai barat pulau Sumatra di bagian utara. Garis imajiner sungai yang membelah pulau Sumatra ini diduga adalah sungai Pasaman di pantai barat dan sungai Rokan di pantai timur. Oleh karena itu, Tacola dan Cocconagara berada di utara garis ekuator.
Cara menginterpretasi informasi ke dalam peta (garis imajiner sungai) serupa ini juga terjadi kemudian pada era Portugis. Dalam peta Portugis (peta yang dibuat oleh Joao de Barros) pulau Jawa dipisahkan oleh garis imajiner sungai. Garis imajiner sungai ini di dalam peta Jawa adalah sungai Tjimanoek di utara dan sungai Serayu di selatan. Masih pada era Portugis, juga ditemukan pada pulau Kalimantan yang dianggap sungai Kapuas (di barat laut) dan sungai Kahayan (di tenggara) bersatu. Interpretasi garis imajiner sebagai garis pemisah Jawa bagian barat dan bagian timur besar dugaan bukan karena hanya semata sungai Serayu di selatan dan sungai Tjimanoek di utara, tetapi diduga karena situasi dan kondisi alam yang yang cenderung masih perairan dangkal (rawa-rawa). Interpretasi ini tampaknya bersesuaian dengan peta tofografi pulau Jawa masa kini berdasarkan peta satelit (SRTM 2004).
Dalam teks Geographia pada peta Ptolomeus juga diidentifikasi nama Barossae sebagai pulau kecil di pantai barat Sumatra di dekat Tacola. Sejumlah peneliti di masa lampau meyakini nama Barossae tersebut adalah nama Baros/Barus yang sekarang. Masih dalam teks Geographia disebut kamper di datangkan dari Aurea Chersonesus. Meski pada masa ini pohon kamper ditemukan di Kalimantan dan Thailand, tetapi pada awal Pemerintah Hindia Belanda perdagangan kamper hanya ditemukan di pantai barat Sumatra. Populasi tanaman kamper ini disebut di wilayah antara Air Bangis di selatan dan Singkil di utara. Oleh karena itu, paling tidak dua komoditi yang diperdagangan di Aurea Chersonesos: emas dan kamper. Aurea sendiri dalam bahasa Yunani kuno adalah emas. Jika nesos adalah pulau dalam bahasa Yunani kuno, lalu bagaimana dengan nama Cherso?
Sumatra (Aurea Chersonesos) bagian utara sebagai simpul perdagangan (emas, kamper plus kemenyan) ke arah barat (India, Persia, Arab dan laut Mediterania/Yunani), juga terinformasikan di Tiongkok. Dari catatan sejarah dinasti Tiongkok Hou Han-Shu (yang disusun pada abad ke-5) diketahu bahwa pada tahun 132 M, pesisir wilayah di timur laut Annam [nama Tiongkok adalah Jih-nan] sudah menjadi titik simpul untuk navigasi dari Laut Selatan. Pada tahun itu di dalam catatan itu disebut raja Yeh-tiao dari luar perbatasan Jih-nan sebuah utusan (duta) untuk memberikan upeti. Kaisar memberikan Tiao Pien kepada raja Yeh-tiao segel emas dan ungu. Yeh-tiao diduga kuat adalah Sumatra, sebab nama Jawa saat itu adalah Yawadwipa. Iabadio dalam bahasa Yunani kuno seperti disebut Prof. R H Th Friederich di atas. Kerajaan Yeh-tiao diduga kuat adalah kerajaan di Sumatra bagian utara. Utusan itu disebut menemui Kaisar di Peking dengan tujuan membuka pos perdagangan di selatan. Lantas apakah sejak ini yang menandai ditemukannya prasasti Vo Cahn yang berasal dari abad ke-3 (di Vietnam)? Yang jelas hingga masa ini, prasasti Vo Cahn dianggap prasasti tertua di Asia Tenggara. Prasasti lainnya ditemukan di pantai timur Kalimantan (Koetai) dan di pantai utara Jawa (Jakarta) yang berasal dari abad ke-5. Dalam catatan Eropa pada abad ke-5 ini disebut kembali nama Barossae dari mana kamper diimpor.
Tunggu deskripsi lengkapnya
Apakah Tacola, Cocconagara Aurea Chersonesus di Malaya? Pulau Tabrobana adalah Kalimantan
Pada tahun 1914 diadakan pertemuan semacam seminar di Inggris tentang perihal peta-peta kuno (lihat Algemeen Handelsblad, 08-04-1914). Pertemuan yang diselenggarakan British Royal Geographical Society di Museum British juga dihadiri oleh ahli peta dari Belanda. Dalam pertemuan ini juga dibahas sejarah kartografi, yang dimulai dari karya geografis Yunani Ptolomeus. Berbagai peta-peta kuno (seperti Italia, Portugis, Inggris) akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ditampilkan dan berbagai buku-buku yang membahasnya juga disertakan yang berasal dari berbagai negara termasuk catatan dari ahli geografi Belanda. Namun soal Taprobana, dimana letaknya dan pulau apa itu tidak terdapat pendapat yang menyakinkan hingga berakhirnya era kolonial Belanda di Indonesia.
Saya beruntung telah mempelajari sejarah pulau Kalimantan. Bahkan semua sudut-sudut pulau Kalimantan. Kebetulan pendekatan yang saya gunakan adalah total sejarah (memahami semua aspek) dengan menggunakan semua sumber data (teks, peta dan lainnya) dan semua metode analisis (intrapolasi dan ekstrapolasi). Dengan begitu saya telah memperluas pengetahuan. Pada fase terakhir dalam mempelajari sejarah pulau Kalimantan itu saya teringat perdebatan lama dalam sejarah peta (yakni peta kuno Taprobana). Saya dengan sendirinya secara otomatis terhubung antara pertanyaan dan jawaban. Ketika saya memperhatikan kembali nama-nama geografi yang terdapat di dalam peta pulau Taprobana, saya semakin terkejut ada sejumlah nama geografi dengan yang saya ingat tentang nama-nama geografi pada pulau Kalimantan. Seperti disebut di atas, metode penalaran pun saya terapkan dalam menghubungkan semua pengetahuan saya dengan merumuskan peta Taprobana. Eureka! Bagaimana merumuskannya adalah sebagai berikut: (1) Sungai-sungai yang digambarkan pada peta Taprobana lebih pendek dari situasi dan kondisi sekarang pulau Kalimantan. Proses sedimentasi menjadi sebab sungai-sungai di Kalimantan lebih panjang dibandingkan dulu (hal ini juga saya temukan di Sumatra dan Jawa); (2) Dengan menarik garis sungai lebih panjang bertemu dengan nama-nama pulau di peta Taprobana yang sudah menyatu dalam peta-peta pada era Portugis (dan VOC); (3) Pulau-pulau kecil yang menyatu dengan pulau Kalimantan memperkuat dugaan saya sebelumnya bahwa terdapat wilayah yang lebih tinggi diantara kawasan sedimentasi (ini juga pernah saya temukan di Kota Padang dan Kota Palembang); (4) Pada peta Ptolomeus ada garis equator yang sesuai dengan posisi pulau Kalimantan; (5) Menarik kesimpulan bahwa peta Taprobana era Ptolomeus adalah sebagian dari wujud fisik peta Kalimantan pada masa ini. Dengan demikian peta Taprobana bukan pulau Ceylon dan juga bukan peta Sumatra.
Setelah saya berhasil menguji pulau Taprobana adalah
pulau Kalimantan (lihat https://poestahadepok.blogspot.com/2021/07/sejarah-menjadi-indonesia-77-peta.html), pengujian berikutnya adalah membuktikan hipotesis bahwa nama Tacola dan Cocconagara
di Aurea Chersonesos dari era Ptolomeus abad ke-2 adalah nama Angkola dan nama
Kunkun yang berada di pantai barat Sumatra. Namun sebelum membuktikan nama Tacola
dan Cocconagara di Aurea Chersonesos dari era Ptolomeus abad ke-2 adalah nama
Angkola dan nama Kunkun yang berada di pantai barat Sumatra, yang terlebih dahulu
dibuktikan adalah menguji garis imajiner sungai pada peta Ptolomeus untuk membedakan dalam peta Area
Chersonesos adalah dua wilayah yang berdampingan antara pulau Sumatra di satu
sisi dan Semenanjung Malaya di sisi lain.
Untuk itu saya gunakan peta era Portugis yang telah dikumpulkan oleh V Obdeijn di dalam tulisan berjudul De Oude Zeehandelsweg door de Straat van Malaka in Verband met de Geomorfologie der Selatan Eilanden yang dimuat dalam jurnal Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, Deel LIX, 1942. V Obdeijn sendiri pernah menjadi Asisten Residen di Indragiri. Peta-peta tersebut adalah peta yang pertama adalah peta pelayaran yang dibuat oleh Pero Reinel tahun 1517. Peta-peta berikutnya adalah peta pelayaran pada tahun 1595; peta yang dibuat salah satu kapal dari ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman (1595-1597) dan peta yang dibuat kartografer Jerman tahun 1605. Dari peta-peta yang dikumpulkan V Obdeijn tersebut terindentifikasi bahwa pulau-pulau di ujung Semenanjung Malaya, mulai dari pulau Bintan hingga Bangka/Belitung merupakan gugusan pulau yang terhubung dengan kedalaman laut yang dangkal (yang perlu dihindari dalam navigasi pelayaran perdagangan).
Dalam peta-peta era Portugis, yang juga merupakan peta navigasi pelayaran perdagangan hanya ada satu celah diantara pulau Bintan dengan ujung Semenanjung Malaya. Ini sesuai dengan laporan seorang Italia Marco Polo yang melakukan pelayaran ke wilayah timur hingga Jepang. Dalam hal ini Marco Polo dapat dikatakan orang Eropa pertama ke timur. Sepulang dari Jepang dan Canton (Tiongkok) pada tahun 1292 berlayar melewari Pentam (Bintan/Batam?) untuk menuju Ferlec (Perlak?).
Ini mengindikasikan bahwa celah pelayaran hanya antara pulau Bintan dan Semenanjung Malaya. Besar dugaan, gugusan pulau antara Bintan dan Bangka/Belitung di masa lampau lebih rapat lagi. Artinya telah terjadi abrasi jangka panjang yang kemudian terbentuk pulau-pulau Bintan, pulau Padang, pulau Lingga, pulau, Singkep, pulau Berhala, pulau Tujuh, pulau Bangka, pulau Lepar, pulau Liat dan pulau Belitung.
Oleh karena itu jika mundur jauh ke masa lampau, dalam
pelayaran yang dilakukan I’tsing pada abad ke-7 tampaknya kurang lebih sama
dengan rute dari Marcopolo enam abad kemudian. Disebutkan dalam catatan
Tiongkok, pada tahun 670 I’tsing berlayar dari Canton ke Bhoja selama 20-30
hari, lalu dari Bhoja ke India melalui Moloyu dan Kieh-cha. Dari Bhoja ke
Moloyu selama 15 hari. I’tsing juga menyebut P'ouo-lou-che berada di sebelah
barat Bhoja.
Dalam catatan Tiongkok dinasti Leang (502-556) disebut nama-nama tempat di pulau emas Kin-lin, Tu-k'un, Pien-tiu of Pan-tiu, Kiu-li of Ktu-tchiu dan Pi-song serta Mo-chia-man. Sementara itu dalam catatan Tiongkok berdasarkan perjalanan I’tsing mengunjungi Sumatra pada tahun 671 (lihat A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago (671-695) ed. J Takakusu, Oxford 1896 dan Prof. P. Pelliot ‘Deux itinéraires de Chine en Inde a la fin du VHF siècle’ di dalam Bulletin Ec. frang. d’ Extr-Or., IV, 1904). I’tsing menyebut Kin-lin sebagai Kin-tchiu (lihat JWJ Wellan, 1934). I’tsing selain menyebut nama Kin-tchiu juga menyebut nama Po-lu-sse dan nama Mo-lo-yu. Dimana tempat Moloyu diperdebatkan, tetapi Po-lu-sse menurut Prof Kern sebagai Baros (I’tsing menyebut Po-lu-sse, yang terletak paling barat, dan berlanjut ke pantai timur). Nama-nama tempat yang disebut dalam catatan Tiongkok pada abad ke-6 mirip dengan nama-nama tempat dipantai barat Sumatra seperti Tu-k'un sebagai Tiku, Pien-tiu of Pan-tiu sebagai Panti, Kiu-li of Ktu-tchiu sebagai Puliu dan dan Pi-song sebagai Sipisang atau Hapesong serta Mo-chia-man sebagai Pasaman. Dalam abad ke-7 disebut nama Po-lu-sse sebagai Barus dan Seng-ho-lo sebagai Sangkilon atau Sangkunur.
Bhoja yang disebut I’tsing diduga adalah Kamboja yang
sekarang. Sementara nama P'ouo-lou-che diduga adalah Barus. Sangat masuk akal
P'ouo-lou-che berada di sebelah barat Bhoja. Moloyu diduga merujuk pada nama
gunung Dolok Malea (di hulu sungai Barumun dan hulu sungai Rokan Kanan) dan
Kieh-cha diduga Kisaran (muara sungai Asahan). Besar dugaan, sebelum I’tsing
sudah ada orang Tiongkok (pada bad ke-6) yang berlayar melalui selat Bintan dan
lalu mengitari bagian utara Sumatra hingga ke pantai barat (Barus dan lainnya).
Masih pada abad ke-7, satu ekspedisi militer yang dipimpin Radja Dapunta Hyang dari Minanga tamuan ke Matajap dan lalu membuat banua. Catatan ini ditemukan dalam prasasti Kedoekan Boekit (682). Sejumlah peneliti pada era Pemerintah Hindia Belanda telah menyimpulkan nama Minanga adalah nama Binanga yang berada di daerah aliran sungai Baroemoen (Padang Lawas). Binanga dalam bahasa Angkola Mandailing diartikan sebagai pertemuan dua sungai. Para peneliti pada era Pemerintah Hindia Belanda juga menyimpulkan bahwa yang dimaksud banua di dalam prasasti adalah benteng. Dalam prasasti Kedoekan Boekit bahasa yang digunakan adalah campuran bahasa Batak dan bahasa Sanskerta.
Dari informasi-informasi di atas, rute pelayaran sejak
abad ke-6, abad ke-7 tampaknya hanya melalui celah pulau Bintan-Semenanjung.
Hal itu juga diikuti rute Marco Polo pada abad ke-13. Setengah abad kemudian, rute Marcopolo ini juga rute
yang dilalui seorang
Moor dari Mauritania/Marocco, Ibnu
Batutah dalam melakukan perjalanan ke timur
hingga ke Tiongkok. Ibnu Batutah sempat bermukim di kerajaan Samudra pada tahun 1345 sebelum ke Tiongkok (lihat Rihlah oleh Ibnu Batutah, 1355).
Pada saat Ibnu Batutah di Kerajaan Samudra pada tahun 1345 penduduknya
sudah beragama Islam. Menurut GE Gerini, Islam pertama kali masuk di Samoedra
antara tahun 1270 dan 1275 (lihat Researches on Ptolemy's Geography of Eastern
Asia. London, 1909). Ini mengindikasikan bahwa Kerajaan Samodra sudah eksis
sebelum tahun 1270. Kerajaan lain yang sudah ada adalah kerajaan Perlak (dengan
mengacu pada laporan dari Marco Polo). Letak Kerajaan Samodra dan Kerajaan
Perlak berbeda.
Dua puluh tahun setelah laporan Ibnu Batutah, di dalam teks Negarakertagama (1365) disebutkan nama-nama tempat termasuk di Sumatra dan Semenanjung. Di pantai timur Sumatra dicatat nama-nama Lampong, Palembang, Djambi, Teba, Darmasraya, Kandis, Karitang, Kampar, Siak, Rokan, Bintan, Aru, Panai, (Padang) Lawas, Mandailing, Perlak, Samudra, Lamuri, Baros.
Dalam teks Negarakertagama (1365) tidak ada nama Bangka, Belitung, Lingga, dan Singkep. Mengapa? Seperti disebut di atas, peta-peta yang dikumpulkan oleh V Obdeijn, apakah nama Bintan mewakili semua gugus pulau, yang mana gugus pulau itu awalnya satu kesatuan daratan? Dalam catatan teks Negarakertagama nama-nama yang dicatat adalah, selain (pulau) Bintan yang disebut di atas, juga nama-nama di Semenanjung, termasuk Tumasik (Singapoera?), Hujung Medini (ujung Semenanjung), Pahang, Kelantan. Muara, Kedah dan lainnya. Intinya, celah atau selat (pulau) Bintan menjadi semacam hub. Gambaran ini juga sesuai dengan rute yang dilalui oleh ekspedisi Cheng Ho, seperti pelayaran pertama (1405–1407) melalui Champa (Vietnam), Jawa, Pa-lim-pong (Palembang?), Man-la-ka (Malaka), A-lu (Aru), Su-man-ta-la (Sungai Karang atau Samudra Pasai), Lam-li (Lambri?), Ceylon, Kollam, Cochin dan Calicut (India).
Dalam konteks inilah kemudian peta Ptolomeus pada abad ke-2 dapat dihubungkan dengan situasi dan kondisi di perairan pantai barat pulau Sumatra bagian utara. Dalam peta Ptolomeus, garis-garis imajiner sungai diduga adalah perairan/laut yang sempit sehingga terkesan di peta Prolomeus (Aurea Chersonesos) antara pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya seakan menyatu. Sedangkan garis imajiner sungai yang membelah (pulau) Sumatra (utara dan selatan) dianggap muara sungai Pasaman yang lebar dan muara sungai Rokan yang lebar adalah selat.
Peta Aurea Chersonesus yang umum ditemukan di internet adalah versi bentuk salinan (diserderhanakan dan lebih ramping). Pada peta bentuk aslinya gambaran Semenanjung Malaya tampak mirip dengan yang sekarang. Sementara pulau Sumatra (yang terbelah dua) di bagian utara digambarkan lebih lebar (daripada yang di selatan). Garis sungai imajiner di utara antara pulau Sumatra dan Semenanjung Malaya berakhir di suatu perairan (bukan di pegunungan seperti bentuk Salinan). Ini mengindikasikan perairan tersebut diduga merupakan laut Andaman, yang mana pada saat itu pulau Sumatra masih terhubung dengan daratan Asia di Burma, namun mengalami abrasi jangka panjang yang membentuk gugus pulau Andaman/Nicobar. Lantas bagaimana dengan bagian peta yang di selatan (seperti segitiga)? Apakah peta ini menggambarkan bentuk gugus pulau pada era Portugis yang dikumpulkan oleh V Obdeijn?
Secara geomorfologis, peta Ptolomeus (Aurea Chersonesos) dalam bentuk asli lebih menggambarkan situasi dan kondisi pulau Sumatra jika dibandingkan dengan sekarang. Mengapa? Bagian selatan Sumatra telah mengalami proses sedimentasi jangka panjang, yang menyebabkan terbentuk daratan yang luas di pantai timur Sumatra khususnya di bagian selatan pulau. Sementara gugus pulau Batam/Bintan hingga ke Bangka/Belitung telah mengalami abrasi jangka panjang sehingga gambarannya menjadi gugus pulau pulau pada era Portugis yang dikumpulkan oleh V Obdeijn, dimana terdapat celah antara pulau Batam/Bintan dengan ujung Semenanjung Malaya.
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur..Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com

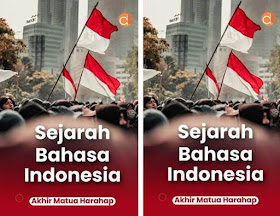











Tidak ada komentar:
Posting Komentar